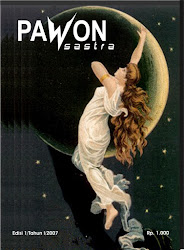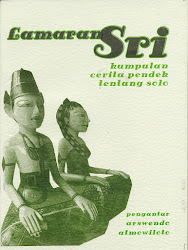Menakar seorang Pramoedya Ananta Toer tidaklah mudah. Membicarakannya, secara tak sadar juga kerap menyeret kita kepada prasangka keberpihakan. Kesan masyarakat sastra terhadap Pram pada umumnya terbagi menjadi dua kelompok. Satu pihak memujinya selangit dan memujanya bak tanpa cela, pihak lain mencercanya habis-habisan tanpa mau menyelami lebih dalam siapakah sebenarnya Pram. Namun beberapa tahun terakhir nampaknya kian kentara upaya untuk menilai nominator Nobel bidang Sastra dan penerima Hadiah Magsaysay ini secara proporsional, lebih fair dan dengan hati yang jernih. Meski maaf, penilaian semacam ini masih sangat jarang kita dengar.
Memang susah untuk memahami Pram secara utuh sebagai sastrawan. Sudut pandang yang dibidik biasanya disertai balutan sastra yang kendati tipis, masih tercium bau kepentingan-kepentingan yang tak jelas relevansinya.
Bicara soal Pram kasusnya mirip-mirip dengan dua nama besar di Republik ini. Ketika ekonomi menjadi panglima, kebanyakan orang yang anti Soekarno hanya menonjolkan kekurangan, kesalahan dan sisi-sisi negatifnya, serta tak mau menyadari bahwa jasa Soekarno besar – bahkan sangat besar – bagi eksistensi NKRI. Jiwa patriotisme dan nasionalisme yang dikobarkannya dulu, terasa sangat dibutuhkan tatkala kondisi negara makin morat-marit dihantam krisis dan bencana, hingga kini.
Demikian pula dengan sosok Soeharto. Mereka yang tak suka akan cenderung melihat ‘tersangka sampai mati’ ini dari sisi gelapnya saja, sementara ada juga yang merasa yakin, pada zaman Orba pun terselip episode-episode yang terbilang manis bagi mereka. Tak mengherankan apabila pemahaman secara hitam-putih sering mengaburkan sensitivitas kita terhadap detail lain dari sang tokoh yang sedang kita perbincangkan. Pada akhirnya, kepicikanlah yang menyeruak, bukan kejernihan.
Politikus dan sastrawan memang berbeda, walau dalam beberapa tujuan bisa saling memanfaatkan. Begitu pula antara politikus dan intelektual, dua ‘profesi’ yang dapat bekerjasama sekaligus bisa saling menjatuhkan. Seorang rekan anggota Dewan pernah berterus-terang, di sela-sela persidangan yang nampak serius atau diserius-seriuskan, para wakil rakyat ternyata suka bercanda. Salah satu kelakarnya, “Seorang intelektual boleh salah, tetapi harus jujur. Sedangkan seorang politikus (termasuk mereka sendiri, anggota Dewan yang terhormat) tidak boleh salah, namun boleh tidak jujur.” Agak susah menebak sejauh mana tingkat akurasi kesesuaian kelakar ini dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Layaknya perjalanan seorang anak manusia, Pram pun mengalami pasang-surut. Pada masa-masa sulit itulah pengarang yang memiliki memori kuat ini dirangkul oleh Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), yang memberikan tawaran cukup menggiurkan, antara lain berupa bantuan finansial dan order penerjemahan. Jadi, untuk urusan ‘dapur’ bagi Pram dianggap telah aman-aman saja. Secara sengaja atau tidak, Pram sering berperan sebagai corong kelompoknya, walau banyak rekan-rekannya yang sangsi, sebab secara ideologi belum tentu pengarang yang ‘keras hati’ sekelas Pram ini dengan mudah dapat dikendalikan.
Namun kenyataannya, tulisan Pram jadi kian garang. Ia memimpin rubrik Lentera yang muncul seminggu sekali di harian Bintang Timur. Di sana ia leluasa untuk menyerang seniman dan sastrawan yang bersebrangan dan berbenturan paham dengannya.Tudingan plagiator sempat hinggap pada Hamka. Dalam hal ini HB Jassin sebagai kritikus sastra berkomentar (dengan disertai argumentasi yang begitu kuat), bahwa Hamka memang sangat terpengaruh Al-Manfaluthi, tetapi jelas-jelas Tenggelamnya Kapal Van der Wicjk bukanlah karya plagiat. Artinya, dalam usaha ‘pembunuhan karakter’ ini memang terdapat unsur non sastranya. Kita tahu, Hamka selain sastrawan juga seorang ulama karismatik.
Tak cukup di sini. Tuduhan kepada Hamka kian ganas hingga ia mesti meringkuk dua setengah tahun dalam tahanan – tanpa proses peradilan – karena diduga makar dan berkomplot untuk membunuh Presiden. Apa mau dikata, pada era tersebut menentang penguasa akan dicap sebagai kontra revolusioner, komunisto phobi atau anti Nasakom. Stempel seperti tidak bisa dianggap main-main.
Budayawan dan sastrawan yang tak setuju dengan pemikiran Pram dan kawan-kawannya pun akhirnya menandatangani Manifesto Kebudayaan yang akhirnya dilarang oleh Pemerintah. Musik ‘ngak-ngik-ngok’ ala Koes Plus yang membius dan lagu cengeng Rachmat Kartolo yang mendayu pun jadi korban pelarangan karena dikhawatirkan mengendorkan semangat revolusi.
Toh, kita tetap tidak bisa menyalahkan Pram seorang. Ada sistem yang lebih besar, dengan otak-otak cemerlang yang merancang konsep dengan rapi serta menerapkannya dalam berbagai strategi guna memuluskan pencapaian keinginan mereka. Barangkali saja mereka memang piawai dalam memanfaatkan nama besar Pram. Kesalahan atau mungkin sesuatu yang mungkin dianggap salah itu, kini telah dibayar tunai oleh Pram. Penulis besar ini harus merasakan hidup terbuang selama sepuluh tahun di pulau Buru.
Tahun 70-an Jendral Sumitro sempat mengunjungi Pram di sana. Kunjungan ini berlanjut dengan penyerahan sebuah mesin ketik manual kepada Pram. Tapi tak seorang pun pernah mengira dari mesin ketik hadiah Jendral Sumitro ini akhirnya lahir novel-novel monumental semacam Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, Jejak Langkah serta beberapa judul naskah lainnya. Rupanya ada kesamaan yang menarik antara Pram dan Hamka. Dalam tahanan yang dilengkapi dengan beberapa model penyiksaan itu – termasuk disundut rokok – Hamka justru bisa menyelesaikan Tafsir Al-Azharnya, pekerjaan yang pasti mustahil ia kerjakan jika berada di luar tahanan. Hamka saat itu memang luar biasa sibuknya berceramah. Pram pun demikian, di tengah tekanan fisik maupun psikis, karya-karyanya yang hebat justru dapat tercipta.
Terlepas dari pernik politik serta segala sebab dan akibatnya, Pram memang seorang penulis besar. Sejak muda hidupnya diabdikan untuk mengembangkan dunia sastra. Tentu ada saatnya pendewasaan itu sedang berproses. Namun bahwa karya-karyanya secara kualitas sangat hebat dan mengagumkan, itu sudah diakui masyarakat sastra. Produktivitasnya pun sulit ditandingi. Tak kurang dari 53 judul buku telah diterbitkan, bahkan sebagian di antaranya sudah diterjemahkan ke dalam 41 bahasa dunia.
Saya jadi ingat sebuah film Nasional yang berjudul ‘Andai Ia Tahu’. Tokoh wanita dalam film tersebut – seorang penulis lepas – suatu ketika terjebak dalam lift macet. Ia hanya berdua saja dengan seorang cowok. Setelah berkenalan dan berbasa-basi sejenak, sang pria tiba-tiba bertanya, “Apakah obsesi utamamu ?” Tokoh wanita tadi menjawab cepat, “Ingin duduk bareng dan ngobrol sama Om Pram!”
Pram tetap seorang manusia, ada kurang dan lebihnya. Kata Agus Miftach (dari BAKIN) yang diberi tugas untuk mengawasi gerak Pram, penulis kelahiran Blora ini memang terlihat tak pernah sholat. Tetapi jika anaknya terlambat sholat, maka ia akan langsung mengingatkannya. Ketika anaknya mau menikah, ia malah menyuruh sang anak dan calon menantunya untuk belajar agama dulu kepada Hamka, ‘sahabat’ yang pernah dijegalnya sekian tahun sebelumnya.
Apa kata Pram tentang kematian? Penulis yang pernah mendapat surat dari Presiden Soeharto serta sempat membalasnya ini menyatakan, “Kelahiran selalu ditunggu orang padahal belum pasti datang. Sedangkan kematian pasti datang, tapi tidak ditunggu.”
Terakhir, kebesaran dan kehebatan Pramoedya Ananta Toer bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan atau dipaksakan. Ia bahkan lebih besar dari yang kita duga. Kiprahnya dalam dunia sastra sangat mencengangkan, dalam makna yang positif. Karya-karyanya luar biasa, banyak tokoh-tokoh masyhur yang mengidolakannya, termasuk mereka yang bersebrangan dengannya. Tentu saja pengakuan ini bukan lantas membenarkan ‘semua’ yang pernah ditempuh dan dilakukannya. Itu persoalan lain yang sebaiknya tidak menjebak kita untuk selalu menoleh ke belakang dan mengaduk-aduk sejarah tanpa mengandung faedah bagi langkah kita ke depan.
Karanganyar, pertengahan Maret 2008