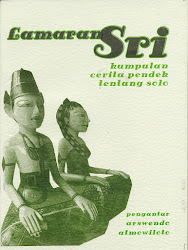Memilih buku-buku yang menurut saya semestinya berumur panjang itu cukup
sulit mengingat banyak buku bagus yang ditulis oleh penulis Indonesia. Namun,
ketika kita diminta untuk lebih fokus dan jujur terhadap pembacaan sebuah buku,
itu menarik sekaligus menantang seberapa kuat buku tersebut punya pengaruh
dalam diri saya, baik untuk kreativitas atau aktivitas berpikir.
Pembacaan buku adalah pengalaman personal, sehingga saya tidak bertanya
kepada siapa pun, tentang bagaimana pendapat mereka mengenai sebuah buku yang
menurut pengamatan saya (seharusnya) berumur panjang. Di sini, saya hanya
mengumpulkan berdasarkan ingatan yang spontan muncul dalam benak saya.
Jadi, urutan di sini bukan maksud saya
memeringkat buku yang saya pilih.
Bumi Manusia (Pramoedya Ananata Toer)
Siapa pun yang mengaku penulis atau pembaca sastra (Indonesia), mestinya
sudah membaca novel tersebut. Karena, bagi saya itu novel penting. Pramoedya
memotret kehidupan Hindia Belanda yang kompleks dengan jernih. Novel
realis-sosialis dengan tokoh Minke untuk menggambarkan TAS (RM Tirto Adisurjo),
jurnalis pribumi pertama dan pendiri Sarekat Priyayi. Buku ini mestinya panjang
umur karena ia mengenalkan tentang pentingnya generasi muda menjadi kritis dan
tajam berpikir. Jangan menyebut diri revolusioner atau aktivis sebuah
pergerakan jika belum membaca novel ini.
Para Priyayi (Umar Kayam)
Sudut pandang lebih dari dua orang tetapi tak kehilangan warna karakter
menjadi salah satu kekuatan novel ini. Semua tokoh memiliki ciri khas dalam
menceritakan dirinya (Lantip, Sosrodarsono, Ngaisah (istri Sosrodarsono), dan
ketiga anaknya). Realitas yang difiksikan, saya menganggapnya begitu. Bukan
hanya menceritakan soal kejawaan, tetapi lebih pada cara penulis menyasar pada
politik, sosial, agama, budaya, sikap hidup dan moral melalui tokoh-tokohnya.
Novel ini pantas panjang umur karena ke-riyayian yang dikenalkan dalam novel
ini adalah mengayomi keluarga (baca: rakyat). Priyayi adalah sikap, bukan
takdir. Ini nilai penting yang pantas diselami oleh generasi kini.
Burung-Burung Rantau (YB Mangunwijaya)
Manusia pasca-Indonesia dan warga dunia. Novel tentang multikulturalisme
yang memikat sejak halaman pertama. Mengajak untuk menukik kedalam batin
tentang kemanusiaan dalam laju teknologi dan “modern” yang tak terhindarkan.
Tentang pahit-manis cinta yang diolah dengan logika. Kisah dan keputusan hidup
para tokoh (Neti, Bowo, Candra) yang dialegorikan dengan burung-burung rantau.
Novel ini mengajak berpikir bahwa kelak suatu hari (dan sekarang sudah dimulai)
bahwa warga negara semakin cair, mobil, dan kita turut tergulung dalam
gelombang itu, tetapi mereka (tokoh-tokoh dalam novel itu) tak kehilangan
identitas. Awalnya, saya cukup kesulitan memilih salah satu judul novel karya
Romo Mangun, apakah Burung-Burung Manyar atau Roro Mendut atau Ikan
Hiu, Ido, Homa atau Burung-Burung Rantau. Tetapi akhirnya saya
memilih yang terakhir. Memang butuh energi ekstra ketika saya menuntaskan novel
ini. Tetapi, saya menyukai kedalam maknanya dan saya pikir, novel ini pantas
berumur panjang.
Canting (Arswendo Atmowiloto)
Novel ini pantas berumur panjang karena merekam dengan baik sebuah era
dimana peristiwa transformasi budaya dan sosial-ekonomi pernah berlangsung (di Solo, Jawa).
Menceritakan bagaimana situasi dan interaksi yang unik dan khas di tempat
pemrosesan batik tradisional, yang kemudian harus meredup oleh hadirnya mesin
produksi yang tak terbendung lagi. Dari generasi Pak dan Bu Bei yang mengolah
perusahaan dengan model lawas, hingga Ni yang bersiap mengolah perusahaan dengan
menyesuaikan zaman.
Tarian Bumi (Oka Rusmini)
Novel ini akan berumur panjang. Paduan antara kentalnya budaya, kuatnya
patriarkhal dan sistem kasta yang kokoh di Bali dan kurang memihak pada
perempuan membuat novel ini seksi dan cool. Cinta itu kuat seperti maut.
Telaga Pidada rela melepas kasta demi cinta, itu adalah bagian yang paling
menyayat karena prosesi pelepasan (penurunan) kasta yang secara simbolik
sungguh memedihkan dan mematik pertanyaan siapakah manusia di hadapan semesta?
Kuantar ke Gerbang (Ramdhan KH)
Potret tentang perempuan yang tak seharusnya dilupakan negeri ini.
Kekuatan dan ketangguhannya dalam menghadapi permasalahan sungguh
menginspirasi. Ia berada di Balik lelaki yang begitu “mengerikan” bagi dunia.
Dua tokoh: laki-laki yang dahsyat dan perempuan yang tak kalah dahsyat. Inggit
dan Kusno (Sang Proklamator) Cinta Inggit adalah semacam tanggungjawab untuk
menjaga Kusno agar tetap hidup dan tak padam semangatnya. Novel sejarah ini
pantas berumur panjang karena setiap generasi harus tahu bagaimana perjalanan
hidup dengan lika-liku perjuangan salah
satu pendiri bangsa ini: Soekarno!
Nyanyian Akar Rumput (Wiji Thukul)
Setiap saya membaca berita tentang perlawanan pada kesewenangan penguasa
di sebuah daerah, saya selalu teringat puisi-puisi Wiji Thukul. Thukul adalah konsistensi terhadap perjuangan
melawan kezaliman pemerintah dan kejamnya kekuasaan. Puisi-puisi yang lantang
bicara tentang hak, demokrasi dan ketertindasan yang lemah. Saya menganggap ini
buku (puisi) penting bukan hanya karena puisi-puisinya yang berani, tetapi juga
penyairnya yang tak boleh dilupakan generasi mendatang.
Ronggeng Dukuh Paruk (Ahmad Tohari)
Saya menyukai bacaan (novel) yang membawa warna lokal dan saya juga
menyukai tarian-tarian khas sebuah daerah. Ronggeng Dukuh Paruk memiliki
keduanya. Novel ini tak hanya mengangkat lokalitas di sebuah Dukuh kecil tetapi
bagaimana tarian dan kesenian (ronggeng) adalah nafas desa itu. Namun sebuah
tragedi bangsa telah menggulungnya tanpa ampun. 1965 adalah masa kehancuran
dukuh kecil bersama kesenian ronggengnya. Saya menganggap novel ini pantas
berumur panjang karena ada sebuah nilai yang tak lekang oleh waktu. Generasi
kini harus tahu agar tidak menjadi generasi ahistoris. Bahwa kesenian, produk
kebudayaan sangat bisa dikontrol bahkan dihancurkan oleh politik dan
kekuasaan.
Pengakuan Pariyem (Linus Suryadi)
Bukankah yang lemah itu selalu (di)kalah(kan)? Apalagi ia seorang
perempuan. Pariyem mewakilinya. Ia sudah kalah sejak lahir. Tempat ia
dilahirkan adalah desa yang kering tandus (Wonosari, salah satu daerah di
pegunungan seribu). Ia anak seorang seniman rakyat yang tentu “sah” untuk
dihabisi kreativitasnya paska 66. Lalu ia menjadi babu pada keluarga ningrat,
kemudian ia dihamili anak majikan, dan puncaknya ia harus menanggung beratnya
meninggalkan anak kandung sehingga ia harus repot bolak-balik dari rumah
majikan ke desa tandusnya. Kekentalan pada bau Jawa menuju modern dalam novel
ini mengabarkan betapa pengaruh dunia luar sungguh mudah merangsek generasi
muda. Melalui novel ini, minimal saya tahu bagaimana tradisi beralih pada
kekinian.
Raumanen (Mariane Katopo)
Novel ini diceritakan dengan sangat cantik dan memikat. Tentang
pergaulan bebas dengan segala konsekwensinya. Menceritakan tentang agama, adat
istiadat dan moral tanpa menggurui apalagi berkotbah. Perjalanan tokoh-tokohnya
diceritakan dengan natural dan lumer. Raumanen menurut saya pantas
menjadi bacaan wajib setiap remaja sepanjang masa.
Sebenarnya saya masih ingin menderet barang 10 judul lagi, tetapi saya
yakin kalau saya menambah 10 judul lagi, pasti saya akan berkeinginan untuk
menambahnya lebih panjang. Pemilihan judul buku yang merupakan pengalaman
personal ini saya harap bisa bertemu dengan pembaca yang sangat mungkin
berpendapat sama dengan saya mengenai sebuah buku. Namun jika berbeda, tentu
bukan soal. Minimal saya tahu pendapat teman-teman pembaca yang pasti tak kalah
seru dalam kelindannya bersama buku-buku.
Kebetulan judul-judul buku yang saya sebutkan di atas adalah buku
(novel) yang saya sukai. Namun saya sempat meneliti dan menginterogasi diri
saya apakah ada buku yang tidak saya masukkan hitungan tetapi saya nilai akan
berumur panjang. Tak pelak, jawabannya adalah novel-novel Fredy S.
Saya sempat tergoda untuk tahu, apakah ada teman-teman pembaca yang
menyertakan salah satu judul novel Fredy S dalam daftar bacaannya, terkait
pemilihan 10 judul buku yang menurutnya berumur panjang. Jika ada, saya sungguh
gembira karena novel-novel Fredy S pernah menjadi kawan perjalanan remaja saya.
Akirnya, saya berharap bisa membaca lebih banyak lagi karya-karya bagus
dari penulis-penulis Indonesia dan berharap dunia semakin mengenalnya. Panjang
umur sastra Indonesia. ||
Dalam dunia buku-buku bacaan, ada banyak buku yang
bagi masing-masing pembacanya meninggalkan kesan mendalam dan bahkan dapat
mempengaruhi pandangan hidup si pembacanya. Buku-buku ini, sayangnya, tidaklah
selalu buku-buku yang mudah ditemukan di toko-toko buku di sekitar kita.
Beberapa dari buku-buku ini bisa saja belum atau tidak jual di negara kita,
atau bisa juga merupakan buku tua yang sudah tidak lagi diterbitkan oleh
penerbit manapun. Tentunya sebagai pembaca buku, kita berharap buku-buku yang
menurut kita sangatlah penting dan berpengaruh ini dapat pula dibaca dan
mengubah hidup pembaca-pembaca lain secara positif di luar sana. Dalam
kesempatan ini, saya akan berbagi perspektif mengenai 10 buku yang menurut saya
seharusnya secara periodik terus dicetak ulang dan akan berumur panjang (tapi
tidak dalam urutan).
Pertama, buku yang menurut saya seharusnya berusia panjang adalah The
Adventures of Tom Sawyer. Buku ini adalah salah satu beberapa karya Mark
Twain yang paling terkenal. Buku ini sebenarnya bukanlah termasuk sastra yang
memiliki kebahasaan yang tinggi dan penuh perumpamaan. Sebaliknya, buku ini
dalam penulisannya menggunakan bahasa Inggris yang sangat tidak baku yang
merupakan aksen Mississippi di zaman penduduknya banyak yang belum memiliki
tingkat edukasi yang baik. Pun buku ini tidaklah memiliki cerita yang rumit
atau penuh drama dan pesan moral-sosial, melainkan hanyalah menceritakan
imajinasi dan kenakalan anak-anak yang sama sekali masih polos, belum
terkontaminasi orang dewasa, dan jiwa penuh kebebasan yang belum terbatasi oleh
pandangan-pandangan kaku orang dewasa. Buku ini layak untuk dibaca baik oleh
dewasa maupun anak-anak, setidaknya menjadi pengingat kita akan kemurnian masa
kecil kita.
Buku kedua yang menurut saya layak berusia panjang adalah Forty Rules
of Love. Novel ini adalah karya penulis Turki yang banyak mengandung
nilai-nilai sufisme. Keunikan buku ini terletak pada gaya penceritaannya yang
paralel. Seorang perempuan yang bekerja sebagai editor harus meninjau suatu
naskah novel yang bercerita tentang pertemuan antara Jalaluddin Rumi dan Shams
Tabrizi. Editor tersebut sedang memiliki masalah rumah tangga dan percintaan
dan kisah dalam manuskrip tersebut memberinya semacam pencerahan. Si editor
akhirnya berkenalan dengan si penulis melalui surel dan akhirnya jatuh cinta
padanya setelah beberapa kali saling berkirim surel. Melalui novel ini kita
akan belajar bahwa di dunia yang penuh ketidakpastian ini, kita harus
senantiasa memilih cinta karena hanya dalam cintalah kita bisa menemukan Tuhan
dan diri kita sendiri.
Yang ketiga dalam daftar saya bukanlah novel, melainkan puisi. Pada
tahun 2010, Avianti Armand menerbitkan buku kumpulan puisinya yang berjudul Perempuan
yang Dihapus Namanya dan memenangkan penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa
kategori puisi. Kumpulan puisi ini terutama mengisahkan tentang perempuan yang
diciptakan Tuhan sebelum Hawa, yaitu Lilith yang sama-sama diciptakan langsung
dari tanah dan Lilith tidak mau jadi perempuan yang tunduk kepada lelaki
sehingga Lilith akhirnya diusir dan dianggap bersekutu dengan setan. Kisah
tentang Lilith sendiri ditemukan pada salah satu gulungan dokumen di Laut Mati,
tapi tidak pernah dikanonisasikan dan justru disembunyikan kisahnya oleh
gereja. Melalui puisi-puisinya Avianti Armand ingin menunjukkan bahwa kehadiran
Lilith tidak bisa dihapuskan oleh beragam upaya, dan Lilith akhirnya selalu
muncul dalam kisah-kisah perempuan yang ada pada Kitab Perjanjian Lama dalam
beragam bentuk. Buku ini agaknya memiliki kesan feminisme yang cukup kuat.
Buku keempat, yang sesungguhnya tanpa perlu saya sebutkan pun pasti
akan terus dicetak ulang, adalah Bhagavad Gita. Bhagavad Gita sendiri
merupakan bahasa Sansekerta yang dalam bahasa Indonesia berarti “Nyanyian
Tuhan”. Buku ini berisi kumpulan syair-syair yang diwejangkan oleh Sri Krisna
kepada Arjuna ketika Arjuna bersedih dan enggan memenuhi kewajibannya sebagai
seorang Kesatria dalam perang Bharatayudha. Dalam wejangannya, Sri Krisna
menjelaskan bahwa dalam keyakinan Sanatana Dharma, Tuhan yang disebut sebagai
Brahman yang tunggal yang sesungguhnya adalah Tuhan yang tidak bisa dijangkau
dan tidak bisa dipahami, sesuatu yang tak terkondisi dan melipuiti ada
sekaligus tidak ada. Brahman kemudian beremanasi menjadi alam semesta sekaligus
isinya serta para Dewa, sehingga setiap yang hidup di dunia ini sesungguhnya
merupakan Atman (percikan dari Brahman). Perbedaan Sri Krisna dan Arjuna (dan
manusia lainnya) adalah Sri Krisna menyadari ada bahwa Brahman ada di dalamnya
dan dia ada di dalam Brahman, sedangkan Arjuna serta manusia lainnya tidak
menyadari hal ini. Sri Krisna juga menjelaskan bahwa sesungguhnya setiap
manusia memiliki caranya sendiri-sendiri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan
dan akhirnya berpulang kembali pada Tuhan, dan karena caranya ini berbeda-beda
maka seseorang hendaklah memenuhi kewajibannya masing-masing, termasuk menjadi
Kesatria yang harus melawan kebatilan.
Kelima dan keenam adalah dua buku yang ditulis oleh penulis Indonesia
favorit saya, yaitu Ziarah dan Kering yang ditulis oleh Iwan
Simatupang. Ziarah ditulis dengan banyak nilai-nilai filsafat eksistensialisme
dengan stilistika yang cukup kompleks, tapi dapat menggali sangat dalam dan
terang tentang sanubari seorang manusia, tentang kemanusiaan itu sendiri.
Melalui Ziarah, pembaca bisa melihat bahwa kebetulan-kebetulan dalam hidup yang
kita alami bisa jadi merupakan kumpulan kejadian yang mengarah kepada satu
keputusan dan jalan hidup, dan akhirnya memaknai pekuburan sebagai panggung
hidup yang sesungguhnya. Kering adalah novel pertama dan sampai saat ini masih
satu-satunya yang pernah say abaca yang dituliskan dengan gaya bahasa
hiperbola. Membaca Kering seolah kita tidak bisa memutuskan apakah ceritanya
adalah realisme atau surealisme. Bisa jadi semua gambaran hiperbolis dalam
Kering adalah bagaimana sesungguhnya benak pikiran kita bertindak dalam alamnya
sendiri, yang hanya terwujud sebagian ke dalam realita kita atas nama batasan
rasionalitas.
Buku kedelapan adalah sastra klasik dari Jepang yang berjudul Yume
Juuya (Ten Nights of Dreams)
karya Natsume Soseki. Ada sepuluh kisah pendek dalam Yume
Juuya, yang masing-masing menceritakan sebuah mimpi yang dialami oleh si
pencerita dalam buku tersebut. Membaca buku ini dapat mengahadirkan nuansa
misterius, horor, kebingungan, kehilangan, harapan, dan juga rasa penasaran.
Perasaan kita benar-benar dibuat melompat-lompat dan campur aduk oleh Yume
Juuya, seolah kita benar-benar baru sedang bermimpi atau baru saja terbangun
dari mimpi dan pengalaman di alam impian itu masih sangat membekas pada jejak
pikiran kita. Buku ini juga sudah pernah dibuat filmnya.
Buku kesembilan menurut saya adalah kumpulan naskah drama dari Tragedi
Yunani. Setidaknya, ada dua kisah dalam kumpulan lakon Tragedi Yunani yang
bagi saya sangat berkesan, yaitu kisah tentang Oedipus Rex dan kisah
tentang Medea. Oedipus Rex bercerita tentang Raja Oedipus yang ketika
lahir telah diramalkan untuk membunuh ayah kandungnya sendiri dan akhirnya
menikahi ibunya. Ayahnya yang merupakan raja akhirnya membuangnya agar tragedi
tersebut tidak terjadi. Namun, Oedipus akhirnya tumbuh besar sebagai anak
angkat dari kerajaan lain dan berakhir membunuh ayah kandungnya dan menikahi
ibu kandungnya sendiri tanpa dia ketahui. Di akhir kisah, Oedipus akhirnya
mengetahui perbuatannya tersebut dan akhirnya meninggalkan kerajaannya dan
mengambil kedua matanya karena menyesal. Medea berkisah tentang seorang istri
yang telah mengkhianati ayah dan kakak kandungnya demi cintanya kepada sang
suami, tapi akhirnya sang suami menikahi seorang putri raja. Medea akhirnya
membalas dendam dengan membunuh sang putri serta sang raja tersebut, lalu
membunuh kedua anak kandungnya sendiri sebagai pembalasan dendam kepada
suaminya. Pada akhirnya baik suaminya maupun Medea adalah yang paling menderita
atas tragedi tersebut.
Terakhir, kesepuluh, buku yang menurut saya layak untuk dicetak ulang
adalah Inteligensi Embun Pagi (IEP) karya Dewi Lestari. Ada alasan
sentimental bagi saya mengapa memilih buku ini sebagai salah satu dari sepuluh
buku yang layak berusia panjang. Menurut saya buku ini bukan sekadar novel,
melainkan bentuk implisit dari rangkuman pengalaman spiritual si penulis.
Melalui buku terakhir dari seri Supernova ini, Dewi Lestari berhasil menuturkan
bahwa manusia adalah “agen dan tubuh-tubuh perantara” dari suatu “Hiperentitas”
yang tunggal ke dunia tiga dimensi kita ini, yang pada suatu ketika umat
manusia terputus koneksinya sehingga manusia lupa asal-usulnya lalu menciptakn
ilusi keakuan. Hiperentitas ini bisa diterjemahkan ke dalam beragam hal; bisa
jadi itu Tuhan dalam konsep agama wahyu, atau mungkin Brahman sesuai agama
Hindu, atau mungkin alien, atau suatu kesadaran kosmik.
Melalui IEP juga dijelaskan bahwa peradaban Sumeria adalah suatu
peradaban manusia yang mungkin paling kuno dan “Tuhan Sumeria atau Alien”
ketika itu mengendalikan manusia agar terus terjebak dalam lingkaran Samsara
(lingkaran tumimbal lahir) dan tidak bisa terbebas mencapai kesadaran kosmik
hingga saat ini. Sebagai tambahan, dalam kisah tersebut ada dua tokoh yang
merupakan metafora dari awal dan akhir, yaitu Alfa dan Ishtar (yang juga
bernama lain Omega). Kedua tokoh ini sejak awal mula sudah saling berkejaran
memutari Samsara agar mereka bisa bersama. Di bagian awal buku ini dibuka
dengan puisi yang mengisahkan tentang Alfa dan Omega yang berpisah dan ingin
menyatu, seperti kerinduan tentang manusia kepada Tuhannya, atau tentang
dualitas antara Samsara dan Nirwana yang untuk mencapai Nirwana (Moksa) sendiri
maka seseorang harus meniadakan dualitas dalam dirinya.
Sebenarnya masih ada buku-buku lain yang menurut saya sama-sama layak
dicetak ulang hingga bergenerasi-generasi kemudian. Namun, pada tulisan ini
saya hanya berkesempatan menyebutkan sepuluh. Mungkin di lain kesempatan saya
bisa menyebutkan buku-buku lainnya yang sejauh ini sangat berpengaruh besar
bagi hidup saya. ||
Sangat gampang sekali memilih dan mencatat sepuluh
buku bahkan lebih, jika tanpa maksud apa pun. Yang bermasalah bukanlah membuat
penilaian terhadap buku, apa pun kriterianya, tapi saat pikiran digerakkan
untuk membuat vonis pemeringkan secara hierarkis: satu karya lebih berbobot,
lebih baik, lebih pantas mendapatkan penghargaan, dan berbagai lebih-lebih yang
lain.
Sepuluh buku bisa saja membutuhkan 100 alasan bahkan lebih sebagai
pembenaran. Dan sering tidak cukup jika kita mengajukan satu buku dengan satu
alasan: entah ketokohan penulisnya, sisi dokumentatif satu karya, pembawa
semangat zaman meski jelek dan tak berbobot, pembentuk arus baru perbukuan, karya
yang seharusnya abadi dan dibaca tiap generasi, dan seterusnya. Sekian
pembenaran itu barangkali bisa berpengaruh pada nasib buku, tapi sungguh tak
ada manfaatnya sedikit pun bagi manusia yang tak membaca buku itu sendiri. Buku
itu tiada, meski dimiliki seseorang tersebut.
Satu huruf seperti A apalagi jika sampai Z, bisa digunakan untuk menulis
berbagai buku yang bisa sangat berbeda, tapi A dan Z tidak pernah mempunyai
nilai hierakis. Di sinilah, seperti diriku saat ini, bisa dengan sedikit enteng
menyebut bahwa sepuluh buku ini pantas diberi umur panjang dan menemui generasi
mutakhir dan masa depan.
***
Apakah RA Kartini (1879-1904) termasuk penulis pertama cerita anak
modern di Jawa? Dalam buku lusuh berwarna hijau dengan judul Buku Pengabdian
Pahlawan Kemerdekaan Nasional Ibu Kartini (1969), panitia tidak cuma
memasukkan kutipan dari surat-surat Kartini yang dianggap penting. Panitia
justru menampilkan karya berjudul Kongso Tjerita Wajang Purwo Buah Karja Ibu
Kartini (1902).
Aku menyebutnya sebagai cerita anak yang aneh: sangat politis yang
bernuasa ‘nasionalitik’. Coba perhatikan paragraf pertama ini: “Basudewo
seorang Radja dari Madura, mempunjai 3 orang istri; isteri jang tertua
melahirkan 3 orang anak, dua orang putera, R Kokrosono seorang bule (albino)
dan R Norojono berkulit hitam, seorang puteri bernama Dewi Brotodjojo, meski
berkulit sawo mateng (bruin) tetapi mempunjai ketjantikan jang luar biasa. Dua
orang isteri lainnja sampai saat itu tidak mempunjai anak.” Di bagian akhir,
terdapat kalimat ini: “Radja sangat bergembira ketika mengetahui bahwa
putra2nja sendirilah jang menolong keradjaannja. Basudewo memanggil 3 orang
putranja bersama Bimo dan Pamadi.”
Aku membayangkan, seandainya Kongso ini bisa dicetak ulang dengan
ilustrasi yang menarik, kepustakaan Kartini tidak hanya terlalu serius tapi
bisa juga bercorak kebocahan.
***
Pada 1951, Suwarsih Djojopuspito selesai menulis buku berjudul Riwayat
Hidup Nabi Muhammad SAW. Buku ini pertama kali diterbitkan pada 1956, entah
oleh penerbit apa, lalu untuk cetakan kedua diterbitkan Pustaka Jaya pada 1976.
Pada kata pendahuluan yang hanya dua paragraf pendek, Suwarsih menuliskan
maksudnya: “Di dalam bahasa Indonesia masih sedikit sekali buku-buku yang
menceritakan riwayat Nabi Muhammad saw dengan kata-kata dan cara, yang sesuai
dengan alam pikiran pemuda dan pemudi jaman sekarang.”
Yang menarik, sebelum diterbitkan, Suwarsih meminta intelektual kondang
H Abdul Malik Amrullah (Hamka) untuk “meminta
pemeriksaan dan bandingan” sebagai pakar sejarah Islam. Namun, “mulanya
belumlah saya acuhkan benar,” kata Hamka. Alasannya agak kurang ajar,
menurutku: “Karena [Suwarsih] sebagai seorang yang berpendidikan Barat, saya
pikir, tentu buku-buku yang dibacanya tentang Riwayat Hidup Muhammad s.a.w.
hanyalah dari sumber Barat. Padahal saya sudah agak lama mendengar nama
pengarang, sebagai seorang wanita yang amat besar minatnya kepada kesusastraan.
Malahan sampai mendapatkan penghargaan yang baik karena suatu karangan dalam
bahasa asing.” Justru, yang aku tahu, maraknya penulisan biografi Muhammad
karena pengaruh ilmu sejarah Barat.
Alasanku memilih buku ini malah karena penulisnya adalah seorang feminis
wanita. Suwarsih kita tahu, seperti diketahui
Hamka, telah menulis novel Buiten het Gareel (Manusia Bebas) yang
ditulisnya waktu berumur 25 tahun dan mendapatkan sambutan menarik dari
kalangan peminat sastra. Yang perlu dicatat, setahuku, hanya dialah sastrawan
perempuan Indonesia yang menulis biografi Muhammad. Namun, sepertinya Pustaka
Jaya tidak bakal tertarik menerbitkannya, tidak bakal seantusias menerbitkan
karya-karya sastra dunia.
***
Salah satu buku sosiologi Jawa klasik terbaik yang pernah aku baca dalam
bahasa Jawa berhuruf Latin adalah Serat Jayengbaya, karya pemuda
Ranggawarsita (Balai Pustaka, 1988), ahli bahasa dan sosiolog yang hidup
sezaman dengan Karl Marx. Imajinasi profesi terliar manusia abad XIX ada dalam
buku ini: mulai angan-angan menjadi penjual kuda sampai kehendak menjadi Tuhan.
Tapi, semua profesi kerja yang diangankan pemuda Ranggawarsita tidak ada satu
pun yang cocok dengan hatinya. Aku membayangkan, jika pemuda Ranggawarsita
hidup di abad XXI, salah satu profesi keinginannya yang tetap tak bakal
dikehendakinya adalah menjadi Tuhan. Betapa repotnya Tuhan di media sosial
jagat maya!
Yang jelas, aku tidak mau menyebut Serat Jayengbaya sebagai “sastra nostalgia”, seperti yang
disematkan pada buku-buku sastra lawas Balai Pustaka. Aku wajib menyebut buku
pemuda Ranggawarsita sebagai buku sosiologi klasik yang cuma salah gaya bahasa:
terlalu lucu dan kocak, bergerak antara realitas dan utopia, sebagaimana Karl
Mannheim membahas di abad XX.
***
Sejujurnya, buku tipis ini pantas terus beredar hanya dengan satu
alasan: romantisme religius seorang suami untuk sang istri. Bilik-bilik
Muhammad, Novelet
Rumahtangga Rasullah SAW, karya AR Baswedan
(pertama kali terbit tahun 1940), sangat memenuhi persyaratan romantis ini.
Buku biografi Muhammad sudah cukup banyak beredar, tapi tidak ada satu pun yang
diawali dengan puisi bernada ala Pujangga Baru. Kita kutip stanza terakhir
puisi dari tokoh Partai Arab Indonesia ini: Nilah, wahai Istri yang mulia!/
Sepantun ratna mutu manikam/ Tanda bersyukur PEMBALAS JASA.../Jadi kenangan
masa nan silam.../penghibur hati...!
Aku membayangkan AR Baswedan membacakan novelet ini pada sang isteri di
kamar mereka. Ah, mesra...
***
Buku ini sangat penting untuk memperingati 100 tahun HB Jassin pada 31
Juli 2017 nanti. Antara Imajinasi dan Hukum: Sebuah Roman Biografi HB Jassin
karya Darsjaf Rahman, yang diterbitkan Gunung Agung pada tahun 1986. Darsjaf
Rahman, berdasarkan pengantar Mochtar Lubis dalam buku ini, adalah seorang
wartawan dan pengarang, yang kenal dekat dengan HB Jassin dan pernah bekerja mengasuh majalah sastra
budaya bersama.
Satu kalimat penting untuk
dikutip: “Hans serba rupa yang merupakan untaian akar-akar halus panjang yang
bergantungan dari dahan-dahan ke tanah. Urat-urat itu memperlengkap wajah
beringin. Hans memang beringin!” Aku membayangkan sastra Indonesia berada di
bawah teduh pohon beringin pusat dokumentasi HB Jassin. Bagi Anda mau
memperingati 100 tahun HB Jassin, segera cari, beli atau fotokopi buku ini!
***
Alasan kali ini sungguh bersifat pribadi: aku belum mempunyai buku ini,
meski sebagian isinya sudah aku baca dan aku kutip: Sumber Terpilih Sejarah
Sastra Indonesia Abad XX, susunan E. Ulrich Kratz (2000). Apakah kamu juga
belum punya atau malah tidak pernah tahu ada buku itu dan tentu tidak mau
punya? Yakinlah, bahwasanya sastra Indonesia abad XX (bukan cuma “sejarah”)
tidak hanya berisi puisi, prosa, dan drama, tapi berseliweran esai sastra yang
bagus dan cerdas!
Buku hampir setebal 1000 halaman ini sungguh keterlaluan pantas untuk
dibaca (calon) pembaca sastra Indonesia modern! Jika kamu mau membaca sastra
Indonesia tapi tidak mau mempunyai dan membaca buku ini, terkutuklah pembacaan
dan bacaan sastramu, hari ini dan kelak! Yakinlah! Aku saja mau bertobat dengan
berdoa harap agar KPG mencetak ulang buku ini! Amin...
***
Dan, kali ini aku sangat merekomendasikan buku pedoman hidup yang sangat
penting di dekade kedua abad XXI: Kesepian– Sumber Ilham yang Kreatif karya WE Hulme. Aku
tidak tahu kenapa zaman edisi mutakhir selalu menggunakan satu kata “jomblo”.
Kata ini tidak puitis, tidak filosofis, dan tentu saja tak terdengar membawa
aura kreatif bagi banyak orang, kecuali Raditya Dika: dari seorang kesepian yang
menulis cara menguburkan anak ayam yang mati terbunuh di tangan mungilnya,
dalam buku Kambing Jantan, yang membuatnya termasyhur sebagai penulis
tragi-komedi, menjadi pembual lucu nan masyhur di jagat kelas menengah muda
Indonesia, sampai menaikkannya menjadi seorang sutradara kondang.
Pasti buku favorit Raditya Dika adalah Kesepian–Sumber Ilham yang Kreatif, yang diterbitkan Cipta
Loka Caraka sejak 1984 dan terus menemani kesepian warga Indonesia sampai 1993.
Kamu jomblo yang perlu kreatif? Bacalah buku agung penting ini! Yakin manjur!
***
Sejak dahulu, di zaman modernku sejak bocah sampai sekarang, aku tidak
pernah belajar ilmu kejahatan dari sang maha pakarnya sendiri. Lalu, pada suatu
hari, aku mendapatkan buku berjudul pas: Iblis karya filosof Dr Mustafa
Mahmoud. Aku merasa, kehidupan kita keterlaluan belajar hal-hal yang baik-baik
saja. Kita justru sangat lupa belajar keiblisan. Tuhan saja menulis tentang
Iblis, masak manusia tidak belajar keiblisan sebagai ilmu sangat penting.
Buku Iblis punyaku hilang satu halaman, di bagian data buku, jadi
aku tidak tahu buku ini terbit tahu berapa. Yang jelas diterbitkan penerbit
Pustaka Mantiq. Perhatikan lima subjudul dalam daftaf isinya ini: “Hakikat
Cinta”, “Iblis”, “Beban Resah”, “Bebas Memilih dan Bukan Ditentukan”, dan
terkahir “Kata-kata yang Tercecer”. Iblis itu apa atau siapa?
Apakah aku termasuk Iblis? Ah, aku ingat kalimat dalam puisi Sapardi Djoko
Damono: dalam dirimu...
***
Dulu, aku agak sedikit kaget waktu mendapat buku berjudul Biografi
Bergambar KH Ahmad Dahlan karya Zaini Ibrohim. Ingatanku langsung pada
“larangan” seni rupa “gambar hidup” dalam persepsi umat Islam. Dulu dalam
“kitab” yang aku baca, ada beberapa gambar makhluk hidup yang garis lehernya
tidak disambung. Aneh! Alasannya: manusia dilarang menggambar makhluk hidup,
bisa dituntut memberikan nyawa. Sekarang, bagiku, si pengucap itu sungguh
keterlaluan tak punya pikiran iman: manusia justru disuruh menjadi Tuhan,
sebagai dzat yang mampu menciptakan nyawa!
Perhatikan maksud buku komik Ahmad Dahlan ini: “Akhir-akhir ini, banyak
kalangan pendidik yang memprihatinkan gejala membanjirnya bacaan bergambar dari
mancanegara. Meski ada yang cukup bermanfaat, namun yang bersifat merusak jauh
lebih banyak jumlahnya.” Maka, buku ini masih pantas untuk dibaca umat Islam,
tentu bukan hanya umat Muhammadiyah.
***
Dan terakhir, buku ini semoga saja menjadi perbincangan publik: Kosmos
karya Carl Sagan yang (telat!) diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia, pada
Desember 2016. Buku ini termasuk buku sains populer yang sangat menarik untuk
dibaca, tidak hanya pada generasi sekarang, tapi juga generasi mendatang.
Satu kutipan penting: “Kosmos baru saja ditemukan kemarin. Selama jutaan
tahun semua orang menganggap jelas tidak ada tempat lain selain Bumi. Kemudian
pada sepersepuluh persen akhir umur spesies kita, di antara masa Aristarkhos
dan kita sendiri, dengan berat hati kita menginsafi bahwa kita bukanlah pusat
dan tujuan Alam Semesta, melainkan tinggal di satu planet kecil dan rapuh yang
tersesat dalam keluasan dan keabadian...”
Maka, kata Sagan, “Fanatisme etnis atau chauvinisme keagamaan atau
kebangsaan menjadi agak sulit dipertahankan bila kita melihat planet kita
sebagai sabit biru rapuh yang meredup menjadi setitik cahaya yang tidak menarik
perhatian di antara kepungan bintang-bintang. Bepergian memperluas pandangan
kita.”
***
Sepuluh buku sudah aku pilih dan tulis sketsanya, dengan sebisa mungkin
sepuluh alasan. Tak semuanya bisa punya kemungkinan untuk tetap akan hadir di
sekian ribu rumah warga Indonesia, lalu mendapati pembacanya yang budiman. Ada
buku yang sudah terkubur di suatu tempat sekarang, tapi barangkali masih bakal
menemukan pembaca ampuhnya di masa depan.
Tiap kali sebuah buku mendapatkan pembaca yang bagus, ia seperti
menemukan seorang sahabat nan kekasih yang bisa diajak ngobrol sepanjang siang
malam, hanya mengenai dirinya. Betapa terhormatnya buku itu. Aku berharap
sepuluh buku yang aku sebutkan menemukan pembacanya yang budiman terhormat di
masa sekarang dan di masa depan. Semoga!
||
Tentang Kami

- Buletin Sastra PAWON
- didirikan dan didukung oleh sejumlah komunitas sastra di Solo, Jawa Tengah. Terbit pertama kali pada Januari 2007. Dalam perjalanan waktu, buletin PAWON meluaskan kegiatan ke wilayah lain diluar penerbitan, yakni mengadakan diskusi, workshop penulisan, kelas menulis, pentas seni dan sastra, menambah lini penerbitan, pendokumentasian kota melalui cerita dan lain sebagainya.
Kategori
Search This Blog
Popular Posts
Edisi Perdana 2007
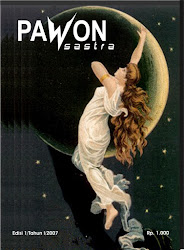
Edisi Ranggawarsita

Edisi No. 35 Tahun II/2012

Edisi Cerpen Solo